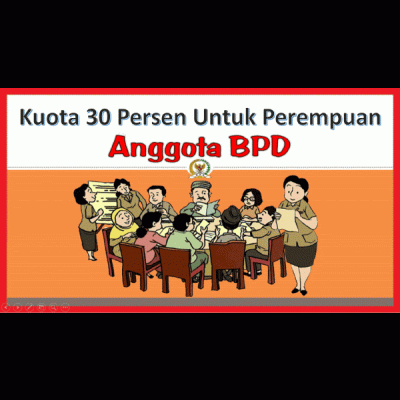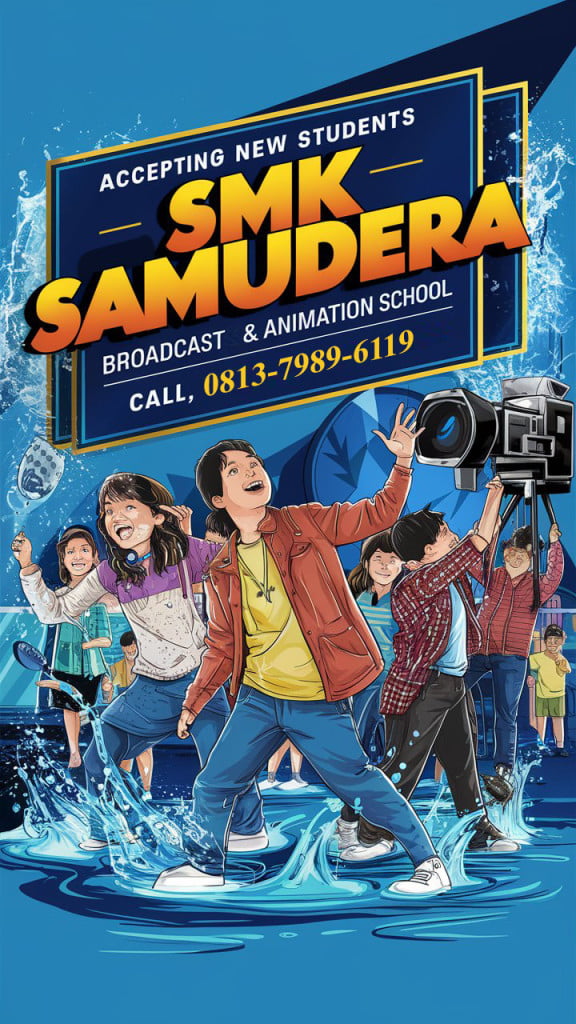Catatan : Riza Allatif
(Behavioral Change Specialist RMC 6 Provinsi Lampung)
 Setiap tanggal 21 April seluruh Rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini. Hari Kartini diambil dari Sosok Raden Adjeng (R.A.) Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu.
Setiap tanggal 21 April seluruh Rakyat Indonesia memperingati Hari Kartini. Hari Kartini diambil dari Sosok Raden Adjeng (R.A.) Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu.
R.A Kartini adalah sosok pelopor persamaan derajat perempuan nusantara yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial dengan keberhasilannya menuliskan pemikirannya secara runut dan detail.
Peringatan Hari Kartini ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964 yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1964 yang didalamnya juga memuat penetapan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
Adapun tujuan peringatan Hari kartini untuk memperingati dan menghormati perjuangan R.A. Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern yang secara khusus terutama dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang.
Peringatan ini selayaknya mengandung makna mendalam mengenai emansipasi perempuan dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus konsisten memperjuangkan keadilan gender.
R.A Kartini juga sangat erat kaitannya dengan isu gender di masa kini. Konsep gender menurut KMK 807 Tahun 2018 merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis.
Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah gender ini pertama kali dikemukakan oleh para ilmuwan sosial, mereka bermaksud untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).
Banyak orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Perbedaan gender ini pun menjelaskan orang berfikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat, baik pada laki-laki maupun perempuan.
Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh RA Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh RA Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidak adilan terhadap kaum perempuan pada masa itu.
PEREMPUAN DALAM BPD
Desa di Indonesia telah ada dan berkembang sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Desa di Indonesia bahkan telah ada sejak Masa Kerajaan di Nusantara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang hingga saat ini terus berkembang. Terus berkembangnya desa juga disertai dengan politik hukum pengaturan tentang Desa yang dibentuk oleh pemerintah sebagai Upaya kemajuan sistem pemerintahan di Desa dalam membangun desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.
Politik hukum dimaknai sebagai landasan atau dasar yang dijadikan acuan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dalam politik hukum sendiri memiliki 2 (dua) sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai arahan pembuatan hukum (legal policy) lembaga-lembaga negara dalam membentuk hukum dan sebagai tolak ukur dalam menilai serta mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan legal policy tersebut.
Dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, Desa telah mengalami berbagai bentuk perkembangan sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dan demokratis. Salah satu tujuan ditetapkannya UU Desa adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri, profesional,efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, sebagaimana arah politik hukum dalam konstitusi.
Diberlakukannya UU Desa menyebabkan adanya kebijakan otonomi desa yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri. Selain itu kemampuan desa otonom juga menjadi syarat untuk dapat membiayai pembangunan di desanya. Pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga perwakilan desa yang berfungsi untuk (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.
Sebagai lembaga perwakilan desa/parlemen desa, BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Mengutip model partisipasi Cornwall (2004)partisipasi perempuan tidak cukup bersifat consultative, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi presence, dimana perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks keberadaan BPD, perempuan perlu memiliki wakilpermanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, model ini disebut sebagai representative, juga mampu memengaruhi proses dan substansi kebijakan publik, disebut sebagai partisipasi influence.
Disahkannya Undang-Undang Desa yang secara tegas menyebut perempuan sebagai unsur dalam musyawarah desa dan keanggotaaan BPD perlu menjadi landasan untuk mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggoatan BPD secara lebih tegas.
BPD adalah merupakan Badan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan startegis. Upaya menggerakkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa diantaranya dapat dimulai melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/2016 tentang BPD telah mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD. Setidaknya satu orang anggota perempuan harus ditempatkan dalam struktur keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal sembilan orang.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di BPD, pertama, tidak adanya instrumen hukum disemua tingkatan baik pusat, daerah dan desa yang mengatur atau memberikan affirmative action (perlakuan khusus sementara) bagi perempuan untuk menduduki kelembagaan strategis di level desa, termasuk di BPD. Kedua, faktor budaya(1) dalam masyarakat yang masih bercorak patriarkis (lebih mengunggulkan laki-laki), perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki, anggapan ini diperkuat dengan dalil-dalil agama yang lebih memberikan privilage atau keistimewaan bagi laki-laki sebagai pemimpin; (2) perempuan di level desa dianggap lebih cocok bersentuhan dengan hal-hal bersifat privat/domestik, bukan hal-hal publik/politik. Hal ini dikarenakan selama lebih dari 30 tahun masa orde baru, perempuan tidak terlatih dan tidak diberikan kesempatan menggunakan daya dan kemampuannya seperti halnya laki-laki dalam mengaktualisasikan dirinya.
Pada masa Orde Baru peran perempuan dilokalisir pada persoalan-persoalan domestik seperti merawat, mendidik dan menjadi pendamping suami, dimana peran-peran tersebut dibakukan dalam kerja-kerja pokok PKK. Perempuan tidak terbiasa berpikir hal-hal strategis dan politik, mereka berkutat pada persoalan-persoalan domestik dan itu diwariskan hingga hari ini. Karenanya, dari sisi kapasitas dan kemampuannya, perempuan di level desa kalah jauh dibandingkan laki-laki.Kondisi ini pada akhirnya membuat perempuan minder, takut dan enggan memasuki ruang politik dan lembaga-lembaga strategis pengambilan keputusan. Ibarat perlombaan lari, garis star perempuan di belakang laki-laki, jika diterapkan aturan yang sama, maka sulit bagi perempuan untuk bisa mencapai garis finish secara bersama.
Persoalan lain adalah praktik dan mekanisme pemilihan BPD yang tidak memungkinkan perempuan mencalonkan diri, apalagi terpilih. Pemilihan BPD dengan mekanisme musyawarah di tingkat dusun dan pemilihan jika tidak terjadi pemufakatan dalam menentukan calon dari masing-masing dusun, dilanjutkan dengan pemilihan di tingkat desa semakin mempersempit kesempatan perempuan. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika diajukan perempuan kerap menolak, baik karena alasan merasa tidak pantas, malu, belum punya kemampuan dan tidak terbiasa di depan publik.
Kondisi di atas yang melatarbelakangi lahirnya affirmative action atau perlakukan khusus sementara melalui berbagai kebijakan agar perempuan dapat menduduki lembaga-lembaga strategis pengambilkan kebijakan seperti halnya DPR dan DPRD. Dalam kontesk BPD penting adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya perempuan dalam keanggotaan BPD.
KEPASTIAN HUKUM PEREMPUAN DALAM BPD
Upaya mendorong perempuan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan publik telah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi juga dibanyak negara lain. Indonesia telah menterbitkan berbagai kebijakan untuk memastikan keterwakilan perempuan. Ini berarti upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis telah diterima sebagai norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang telah lahir dan bisa menjadi rujukan dalam mengatur keterwakilan perempuan di Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi MengenaiPenghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) dalam lampiran:
Pasal 2 huruf f:
Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untukmengubah, menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaandan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita.
Pasal 3:
Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, termasukmembuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidangpolitik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuanwanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakandan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok dasar persamaan denganpria.
Pasal 4 ayat (1):
Pembentukan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan khusus sementara olehnegara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan de facto antarapria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalamkonvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaanstandar-standar yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dantindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan, persamaan kesempatan danperlakuan telah tercapai.
Pasal 7:
Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untukmenghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupanbermasyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas dasarpersamaan dengan pria, hak:
- untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan berkemampuanuntuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih masyarakat;
- untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah danimplementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan danmelaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan;
- untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulannon pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara;
Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 49
- Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, danprofesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaanpekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancamkeselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksiwanita.
- Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya,dijamin, dan dilindungi oleh hukum.
Keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 54ayat (1)
“……. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antaralain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokohpendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan,kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompokmasyarakat miskin.
Pasal 58 ayat 1
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desaditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah,perempuan, penduduk, dan kemampuan KeuanganDesa.
Kelima, Kebijakan terkait
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Lampiran di bagian Umum angka 4:
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. - Tap MPR No.VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
Angka 10:
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” huruf (b);
Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakandasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing Tahun 1995.
Keenam. Perubahan Kedua Undang-Undang tentang desa pada Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
REKOMENDASI
Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan di desa begitu penting untuk menjamin adanya wakil perempuan dalam lembaga perwakilan untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan, hal ini juga seiring dengan pentingnya akan pemberdayaan perempuan di desa melalui peran, tugas dan fungsi dari BPD. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam BPD telah jelas tertuang pada Perubahan Kedua Undang-Undang tentang desa dalam pasal 56 telah menjamin persamaan kedudukan Perempuan dalam Badan Permusyawatan Desa. Sangat jelas anggota BPD di setiap desa wajib memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang desa adalah Hadiah dan sekaligus menandai terbukanya pintu partisipasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan desa. Hal-hal yang menjadi Agenda Penting berikutnya adalah :
- Mendorong Munculnya Regulasi Daerah terkait BPD yang pro terhadap keterwakilan Perempuan pada BPD
- Memperbaiki sistem atau pola rekruitmen BPD sehingga dapat menampung masukkan kuota perempuan dalam calon dan keanggotaan BPD
- Memasukkan kuota perempuan dalam panitia pemilihan anggota BPD
- Menjamin keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan BPD baik langsung maupun musyawarah mufakat.
- Penguatan dan Peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota BPD agar mampu berperan maksimal sesuai aturan perundang-undangan
Sumber Pustaka:
- Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa, 2016. https://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/
- Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan Desa Karangsari, 2019. https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/986/pemilihan-bpd-keterwakilan-perempuan-desa-karangsari
- Diskusi Mewujudkan Partisipasi Perempuan di BPD, 2019, https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/437/diskusi-mewujudkan-partisipasi-perempuan-di-bpd